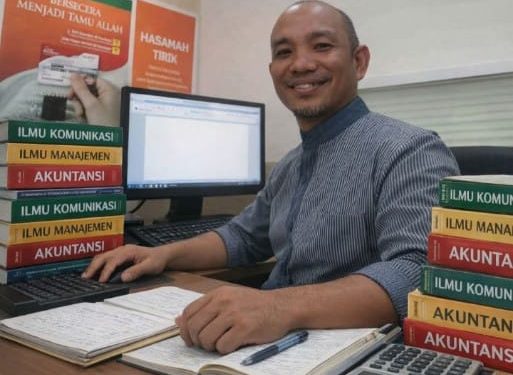Penulis: Abu Al-Faqir
Di era digital yang kian riuh, muncul pola komunikasi yang sekaligus menarik dan mengkhawatirkan: seseorang tampil lantang mencaci, menyerang, dan merendahkan di ruang publik, namun berubah menjadi pemohon di ruang privat.
Di depan layar ia menjelma singa, di belakang layar ia menjadi pengemis akses. Paradoks ini bukan hanya soal etika, tetapi dalam perspektif Manajemen Komunikasi adalah krisis konsistensi pesan dan kegagalan mengelola modal relasi.
Media sosial telah menjadi panggung frontstage, ruang performatif tempat citra dibangun dan persepsi diperebutkan. Sayangnya, panggung itu kerap dipakai bukan untuk membangun pengaruh, melainkan menebar kegaduhan.
Ujaran yang seharusnya menjadi alat dialog berubah menjadi peluru psikologis yang ditembakkan tanpa tanggung jawab. Ironisnya, mereka yang paling nyaring menyerang di ruang publik seringkali adalah orang yang sama yang kemudian menghubungi secara pribadi untuk “minta tolong,” “minta rekomendasi,” atau “minta akses” kepada pihak yang sebelumnya mereka hina.
Dalam teori komunikasi organisasi, perilaku semacam ini dikenal sebagai hypocritical communication behavior ketidakselarasan antara yang diucapkan dan yang sebenarnya diinginkan. Manajemen komunikasi menegaskan bahwa kepercayaan tidak hanya runtuh karena pesan yang salah, melainkan karena ketidaksinkronan antara pesan publik dan privat. Saat seseorang menyerang di frontstage tetapi meminta di backstage, ia sedang membakar jembatan kepercayaan yang justru ia perlukan.
Komunikasi strategis sejatinya adalah seni menata pesan, emosi, dan relasi secara sadar. Emosi bukan musuh, tetapi instrumen yang harus dikelola, bukan diumbar. Dalam organisasi, pemimpin yang matang memahami bahwa kontrol emosi berarti kontrol pesan, dan kontrol pesan berarti kontrol pengaruh. Sebaliknya, komunikator yang reaktif hanya menjadi komoditas algoritma ramai di timeline, tetapi bangkrut di trustline.
Ini bukan ajakan untuk menutup pintu kritik. Kritik adalah vitamin demokrasi; penghinaan adalah racun relasi. Komunikasi yang sehat boleh tegas, bahkan keras dalam argumentasi namun tidak liar dalam ujaran. Ketegasan membangun wibawa, sedangkan penghinaan meruntuhkan masa depan. Dalam manajemen komunikasi, modal terbesar bukanlah viralitas suara, melainkan kredibilitas relasi.
Akhirnya, waktu akan menjadi selektor alami para komunikator. Yang bertahan bukan yang paling keras nadanya, melainkan yang paling jernih, konsisten, dan bermartabat pesannya. Sebab komunikasi bukan hanya tentang menang di layar, tetapi tentang bertahan dalam kepercayaan.